Penelitian tidak ilmiah ini berawal dari pertanyaan, kenapa Dedens lebih acceptable dibanding Kim Jon Rue padahal keduanya sama-sama sengak dalam berbicara. Acceptable dari sisi apa sih? Dalam hal kerelaan (circle saya) menyebarkan tulisan mereka. Kedua artis ini unik, mereka suka berkata kalau mereka ini cinta tanaman dengan cara hobi menyiram taman, padahal mereka membuat tanaman jadi kebanjiran, lalu busuk, dan tanaman pun jadi ikut-ikutan sengak. Tapi entah kenapa secara realita di circle saya dan beberapa kawan lainnya tulisan-tulisan Dedens itu sharability-nya lebih tinggi. Anehnya lagi dalam pandangan saya, orang yang mencibir orang lain yang men-share postingan justru dikategorikan (maaf) “bodoh” dan “tolol”, (dan saya lumayan setuju). Tapi orang yang mencibir ini malah share postingan Dedens, di tema yang sama, duh, kan saya jadi tepok jidat. Bahkan teman saya bilang, “orang yang menghina orang lain tolol tapi berpihak kepada ketololan lain, itu tolol kuadrat atau gimana?”. Maka dari itu saya penasaran untuk melihat apa yang membedakan mereka. Untuk melihat fenomena ini, saya menggunakan bayesian statistik.
Kenapa saya menggunakan bayesian statistik? Karena dengan bayesian saya bisa melihat probabilitas seseorang memandang sesuatu terutama terhadap beliau-beliau ini. Selain itu, bayesian statistik memberikan kesempatan untuk menempatkan subjektivitas pada perhitungannya. Agar lebih jelas, saya mulai dengan formulanya. Tenang, saya tidak akan memunculkan perhitungan rumit didalamnya, hanya hitungan-hitungan dasar. Kalaupun ada yang rumit biarlah itu menjadi sebuah blackbox. Ready? Ok, here we go. Start with the formula. Dasar bayesian statistik memiliki rumus seperti berikut :
Posterior = Function(Prior, Likelihood)
Prior dan Likelihood dimasukan ke dalam sebuah fungsi, sehingga outputnya adalah Posterior. Hmmmm, bahasanya lumayan tidak manusiawai untuk masyarakat Indonesia. So, insted of using Posterior, Prior, and Likelihood, I prefer using several new terms, sehingga formulanya menjadi :
AfterBelieve = Function(CurrentBelieve, ObservedBelieved)
Apa itu?
CurrentBelieve = Bagaimana keyakinan kita sekarang terhadap sesuatu. Contoh : Bagi pro Jokowi, kebijakan Jokowi yang baik rasionya adalah 80%, maka si pro meyakini probabilitas Jokowi berbuat baik adalah 0.8. Atau bagi yang kontra Jokowi, si kontra meyakini probabilitas Jokowi berbuat baik hanya 0.2.
ObservedBelieve = Bagaimana keyakinan kita memandang satu atau lebih kejadian, alias kejadian yang sedang diamati. Contoh : Kebijakan Jokowi tentang Tax Amnesty : Bagi yang pro, 100% baik. Bagi yang kontra, hmmm, jelek sih, tapi gak jelek-jelek amat, ya sudah 30% baik.
AfterBelieve = Bagaimana keyakinan kita terhadap sesuatu setelah mengamati suatu kejadian dimana sebelumnya kita telah mempunyai suatu keyakinan. Semakin banyak ObservedBelieve yang kita peroleh, semakin kuat afterBelieve yang akan terbentuk. Contoh : Pro Jokowi sebelumnya meyakini kalau kebijakan Pak Jokowi 80% baik. Setelah keluar Tax Amnesti, keyakinan kita terhadap Jokowi menjadi 85% karena yang Pro Jokowi memandang Tax Amnesty 100% baik.
Note : Jika kita akan mengamati kejadian yang baru lagi setelah kejadian di atas terjadi, maka CurrentBelieve kita harus diupdate menggunakan sebuah fungsi tertentu. Contohnya, Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan biaya STNK yang dinilai oleh Pro Jokowi 60% baik. Kejadian STNK ini kita kategorikan ObserverdBelieve. Maka CurrentBelieve yang digunakan bukan lagi yang 80% tapi yang sudah diupdate setelah kejadian Tax Amnesty, dimana sebut saja setelah diupdate menjadi 87%.
Bagaimana? Paham? Semoga paham. Lalu, saya menerapkan formula ini pada beliau-beliau ini. Beberapa bulan lalu saya mengamati postingan mereka. Saya mengamati sekitar 30 postingan, dimana tiap 5 postingan saya kategorikan menjadi 1 ObservedBelieve, dan masing-masing postingan saya nilai secara subjektif lebih banyak positifnya atau negatifnya, kalau positif saya beri poin satu, kalau negatif 0. Misal dari 5 postingan ada 3 positif, maka nilai positifnya adalah 3. Sayangnya, ternyata pengamatan saya yang tersimpan hanya berapa kali postingan positif yang mereka lakukan, sehingga untuk perhitungan CurrentBelieve dan AfterBelieve dilakukan dengan cara mengestimasinya, ya sebut saja dikira-kira tapi dengan penuh pertimbangan, (sedang speed writing, hehe). Saya mulai subjektivitas saya ke mereka dengan mengeset CurrentBelieve saya sebesar 0.5 terlihat pada observasi 1, sebut saja netral. Maka, apa yang terjadi ? Berikut hasil pengamatan saya. Pusing? Abaikan saja, langsung masuk ke penjelasan saja.
Berikut data Dedens
| observasi |
jumlah
postingan |
positif |
total
Positif |
total
Negatif |
current
Believe |
observed
Believe |
after
Believe |
| 1 |
5 |
4 |
1 |
1 |
0.5 |
0.8 |
0.8 |
| 2 |
5 |
3 |
5 |
2 |
0.8 |
0.6 |
0.7 |
| 3 |
5 |
1 |
8 |
4 |
0.7 |
0.2 |
0.5 |
| 4 |
5 |
3 |
9 |
8 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
| 5 |
5 |
3 |
12 |
10 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
| 6 |
5 |
1 |
15 |
12 |
0.6 |
0.2 |
0.5 |
Lalu ini data Kim Jon Rue
| observasi |
jumlah
postingan |
positif |
total
Positif |
total
Negatif |
current
Believe |
observed
Believe |
after
Believe |
| 1 |
5 |
2 |
1 |
1 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
| 2 |
5 |
2 |
3 |
4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
| 3 |
5 |
1 |
5 |
7 |
0.4 |
0.2 |
0.3 |
| 4 |
5 |
3 |
6 |
11 |
0.3 |
0.6 |
0.4 |
| 5 |
5 |
2 |
9 |
13 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
| 6 |
5 |
1 |
11 |
16 |
0.4 |
0.2 |
0.4 |
Ya, ternyata dari perhitungan subjektivitas saya Dedens lebih positif dibandingkan Kim Jon Rue walaupun cuma beda 0.1 probabilitasnya. Tapi ada yang menarik dari data Kim Jon Rue dan Dedens ini. Jika melihat data Kim Jon Rue, beliau ini polanya aggresif, jarang sekali ia mendapat skor ObservedBelieve di atas 0.5. Lihat saja skor positifnya, 2, 2, 1, 3, 2, 1. Dia hanya sekali mendapat persetujuan mayoritas positif dari saya. Coba bandingkan dengan Dedens, dia beberapa kali mendapat persetujuan positif dari saya. Ketika AfterBelieve-nya sangat tinggi, dia tiba-tiba bermain sangat sengak, lihat saja dari 3 menjadi 1 sejumlah 2 kali. Bagi saya, Dedens ini sepertinya pandai memainkan tempo. Dia membuat saya berpikiran bahwa dia pembawaannya selalu positif, lalu tiba-tiba sengak, seperti alunan Bethoven Symphony 5. Ketika sentimen mulai negatif, ia membuat hal-hal positif lagi. Walaupun pada akhirnya currentBelieve saya semakin kuat bahwa beliau ini sengak kalau bicara, terlihat dari selisihnya dengan Kim Jon Rue yang cuma beda 0.1 itu. Btw, 0.4 sama 0.5 itu relatif tinggi, ini dikarenakan saya tesnya dengan sampel yang sedikit, hanya 30. Kalau 300 atau 1000 postingan mungkin AfterBelieve saya bakal jadi 0.2 sama 0.3.
Well, itu perhitungan yang hanya menggunakan subjektivitas saya, tentu akan berbeda dengan perhitungan orang lain. Hasil yang lebih aktual sepertinya akan lebih terlihat jika dilakukan dalam jumlah besar pesertanya dan postingannya dan dalam jangka yang panjang. Tertarik untuk mencoba ?

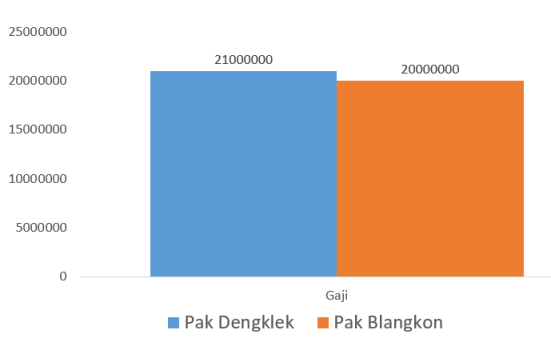
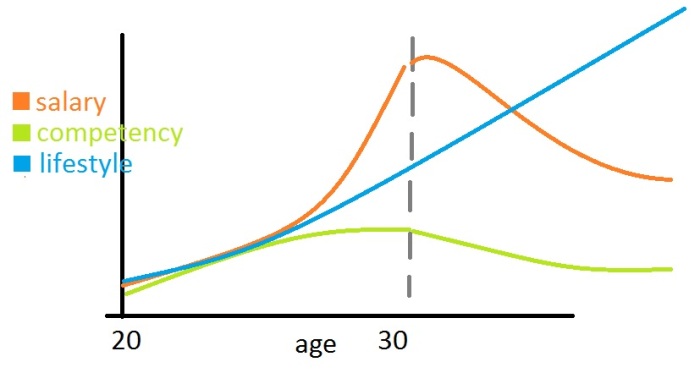
You must be logged in to post a comment.